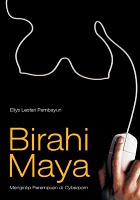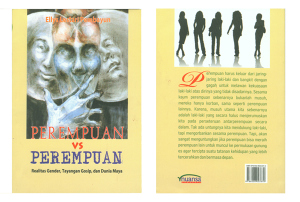Women Social Responsibility terhadap Buruh Migran Perempuan di Indonesia: Suatu Pendekatan Komunikasi Partisipatif
Oleh Ellys Lestari Pambayun
Dosen FISIP Prodi Ilmu Komunikasi UNAS Jakarta
Realitas Buruh Migran Perempuan Indonesia
Dalam era pembangunan di Indonesia, dasawarsa 1970-an ditandai oleh banyaknya perubahan, termasuk perubahan pola kerja kaum perempuan. Mayling Oey (2004:127) menyebutkan tiga faktor penyebabnya. Pertama, pertumbuhan penduduk usia kerja yang terus menerus tinggi, akibat kesuburan atau kehamilan penduduk di masa lalu, yang menciptakan tekanan penduduk, khususnya di Jawa. Kedua, kepesatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dasawarsa sebelumnya. Ini dibuktikan oleh kenaikan tahunan sebesar 7,3 persen dalam produk domestik bruto (PDB) antara 1971 dan 1980. Ketiga, meskipun faktor penyebab khususnya tak dapat dipastikan, namun dapat dikemukakan bahwa kemajuan ekonomi yang pesat itu telah mendorong perubahan sosial yang begitu cepat.
Perubahan sosial ini memunculkan realitas berubahnya orientasi kerja perempuan, yang semula cenderung memiliki moto “makan tidak makan asal kumpul” menjadi “berkumpul terus kapan majunya?”. Pola pikir atau orientasi inilah yang membuat perempuan Indonesia memiliki keberanian meninggalkan keluarga demi perubahan hidup keluarganya. Jadilah mereka buruh migran perempuan di luar negeri. Realitas yang lebih menakjubkan adalah bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah pekerja migran terbesar. Harian Kompas menyebut ada sekira enam juta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan 80 persen di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 70 persen di antaranya bekerja sebagai pembantu rumah tangga (Kompas, 14 Nopember 2009).
Besarnya jumlah pekerja migran perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia ternyata tidak sebanding dengan nasib dan masa depan mereka sebagai pahlawan devisa bagi negara. Bahkan, seringkali mendapat perlakukan tidak adil berupa penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Perlakuan kurang pantas yang diperoleh TKW Indonesia seolah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pahlawan devisa tersebut. Potret ketidakdilan terhadap TKW yang mengadu nasib di luar negeri semakin menambah luka dan harga diri bangsa Indonesia semakin terinjak-injak oleh bangsa lain.
Di Malaysia, peristiwa tragis tentang kekerasan pada buruh migran perempuan Indonesia itu pernah membuat geger seluruh publik tanah air. Cerita yang sama juga pernah manguras rasa kemanusiaan kita di Hongkong. Peristiwa memilukan itu juga ternyata kerap terulang di negara-negara Timur Tengah yang menjadi tempat favorit para TKW. Rayuan riyal sering berubah menjadi bisa ular yang kemudian menjadikan para TKW seperti budak belian karena sering diperlakukan di luar batas kemanusiaan.
Kasus penyiksaan buruh migran perempuan yang mengadu nasib di luar negeri, seolah tak pernah berhenti mewarnai hiruk-pikuk persoalan bangsa. Tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang mengalami hukuman mati di Arab Saudi karena membunuh majikan yang kerap menyiksanya secara fisik kali ini bernama Rohyati. Sebelumnya, Sumiati asal Dompu Bima Nusa Tenggara Barat terluka parah akibat digunting majikannya di Madinah, Arab Saudi. (okezone.com)
Penganiayaan juga dialami oleh Kikim Komalasari, seorang TKI asal Cianjur, Jawa Barat, yang bekerja di Arab Saudi. Bedanya, kalau Sumiati masih hidup, Kikim disiksa majikannya sampai tewas. Jenazahnya pun dibuang ke tong sampah. Konon, ia dibunuh majikannya tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Informasi mengenai kematian Kikim disampaikan oleh seorang relawan Posko Perjuangan TKI (Pospertki) PDI-Perjuangan di Kota Abha. sumber: (http://arsip.indipt.org) Ini membuktikan fungsi monitoring dan pengawasan TKI yang dijadikan alat meminta tambahan anggaran BNP2TKI maupun Kemenakertrans pada DPR, nol besar dan tak tepat fungsi. Pernyataan pemerintah yang menyatakan tentang rendahnya persentase masalah yang dihadapi TKI, yakni 0,01 persen, juga lebih menunjuk makna retorika politik. Ada upaya menyederhanakan masalah melalui angka. Sejatinya, perlakuan tak manusiawi seorang TKI saja, cukup bagi negara memerjuangkannya. Tak manusiawi menunggu angka signifikan. Bukankah negara berkewajiban melindungi keselamatan setiap warga negara? Pemerintah tak memiliki proper sense of humanity. Pemerintah juga tak memberi keyakinan bangsa untuk berani tegas dan menekan negara “importir” TKI.
Penyiksaan dan eksploitasi terhadap buruh migran perempuan ini terjadi karena salah satu faktor utamnya adalah kemiskinan. Sebagai kaum miskin, perempuan tidak memiliki kemampuan melawan, menjadi lemah, dan pasrah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 70 persen dari total jumlah orang miskin di Indonesia adalah perempuan. Russo dan Denmark (1984) menyatakan bahwa di dunia pada tahun 1981 saja representasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 63 persen. Inilah bentuk feminisasi kemiskinan yang merupakan masalah yang sangat serius. Selain itu, banyaknya keluarga yang bertopang hidup pada kaum perempuan. Mereka bekerja dengan gaji yang sama sekali tidak bisa membantu mengangkatnya dari jurang kemiskinan. Pada tahun 1987, di dunia dari sekitar 4,7 juta pekerja perempuan, 65 persennya bekerja di sektor penjualan dan mejadi pelayan. (Unger dan Crawford, 1992:456)
Sebelumnya, Migrant CARE pada tahun 2009 melaporkan bahwa terdapat 5314 kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Dari 5314 kasus itu, 97% dialami oleh perempuan, sementara hanya 3% yang dialami laki-laki. Lalu, terdapat pula 1018 kasus kematian buruh migran di tahun 2009. Dari 1018 kematian tersebut, kasus kematian karena kecelakaan kerja berjumlah 90 kasus, sementara kematian karena kekerasan berjumlah 89 kasus. Adapun kematian yang tidak diketahui sebabnya berjumlah 268 kasus. (http://tkw-korea.blogspot.com)
Wahyu Susilo mengatakan bahwa diskriminasi buruh migran perempuan Indonesia tidak mengenal tempat. Di dalam negeri, mereka tidak saja diperlakukan sebagai komoditias dan warga negara kelas dua, mereka juga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan. Terminal III Bandara Soekarno Hatta merupakan tempat nyata dari bentuk diskriminasi terhadap buruh migran perempuan Indonesia; dengan memisahkan mereka dengan penumpang umum lainnya. Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, buruh-buruh ini juga diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Karena waktu kerja yang ketat, banyak buruh migran dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. (Jurnal Perempuan, Edisi 26 tahun 2002: 54)
Fenomena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor domestik pernah diungkapkan Nievva Guttek (1987) yang menyatakan bahwa kebanyakan perempuan bekerja di bagian pelayanan di mana pekerjaan mereka tidak jauh berbeda saat mereka di rumah, seperti membersihkan rumah, menyediakan makanan, mengasuh anak, dan sebagainya, baik di rumah majikan maupun rumah sakit atau kantor. Ini dikarenakan adanya stereotip feminin yang melihat pekerjaan perempuan sebagai produk alamiah bukan didasarkan pada kompetensi individual. Pemikiran ini tentu saja menguatkan terjadinya devaluasi terhadap pekerjaan perempuan. (Unger dan Crawford, 1996:452)
Karena itu, stereotip feminin dalam persoalan buruh migran perempuan sebagai persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dan isu jender. PRT migran berada pada relasi kuasa yang amat timpang karena mereka perempuan dan bekerja dalam sektor informal di rumah tangga. Di rumah, perempuan calon buruh migran, terutama yang masih muda, kerap mengalami pemaksaan dari lingkungannya yang miskin untuk segera bekerja. Pendidikan yang rendah menyebabkan peluang kerja yang tersedia biasanya sebagai PRT. Begitu keluar rumah, mereka menjadi korban perekrut tenaga kerja. Di tempat kerja, status pekerja informal membuat mereka tak memiliki posisi tawar dengan majikan. Pemerintah pun tidak mendukung perlindungan terhadap PRT karena enggan mendukung konvensi ILO tentang perlindungan terhadap PRT. (http://www.trunity.net)
Indikasi tersebut sangat Jumlah menjadikan buruh migran Indonesia yang sebagian besar perempuan semakin terperangkap dalam konstruksi masyarakat patriarkis yang memang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender. Kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, perkosaan yang mengakibatkan kematian adalah yang sangat sering dialami buruh migran perempuan Indonesia. Pemerintah memang akhirnya telah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang terkait dengan diskriminasi (misalnya, CEDAW/Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan berbagai Konvensi ILO). Tapi, implementasi kebijakan masih mengandung semangat diskriminasi bahkan kebijakan penempatan buruh migran sudah mengarah pada kebijakan perdagangan manusia. (http://www.tempointeraktif.com)
Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah UU yang melindungi TKI di luar negeri yang diperkuat oleh ratifikasi Konvensi Migran 1990. UU yang berlaku sekarang tidak sekadar diskriminatif terhadap TKI, tapi juga terhadap perempuan. Karena, 75% pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri berkelamin perempuan.
(http://news-monitor.ecosocrights.org)
Secara khusus, pengalaman yang menunjukan betapa rentannya Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual ini seharusnaya mendapat perhatian yang ekstra khusus. Meskipun, kasus Nirmala Bonat beberapa saat lalu, tergolong kasus TKW yang telah mendapatkan perhatian khusus. Namun, tidak sedikit kasus, penyiksaan, pelecehan seksual dan upah kerja tidak dibayar luput dari perhatian publik. Sebagian kasus tersebut memang belum merepresentasikan problem pekerja migran yang sesungguhnya, karena bisa jadi melebihi penderitaan ‘Nirmala’ lainnya yang tidak sempat diliput media. Begitu pula, kasus-kasus TKW yang terkena hukuman mati akibat hubungan seks di luar nikah di Timur Tengah mestinya merupakan persoalan nasional. Namun, upaya pemerintah terkesan parsial dan musiman. Status pekerja migran, termasuk yang ilegal timbul disebabkan oleh karena ketidaksesuaian kompetensi pekerjaan (mismatched of qualification) yang tersedia dan PRT di luar negeri telah menjadi penyebabnya. Padahal tidak seorangpun menafikkan betapa besarnya devisa para buruh migran perempuan ini bagi negara. (http://jawahirthontowi.wordpress.com)
Oleh karena itu, tulisan ini hendak memaparkan urgensi pendekatan komunikasi yang strategis dan partisipatif dalam penanganan pekerja migran perempuan (TKW), agar praktik-praktik diskriminatif dan eksploitatif yang menginjak-injak harga diri mereka sebagai perempuan dapat direduksi, bahkan dieliminasi.
Tindakan Transformasional Perempuan
Arah pembangunan, kebijakan pemerintah, dan hukum yang seringkali tidak berpihak pada Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Indonesia harus dijadikan sebuah tantangan bagi para perempuan untuk mengalirkan energi dan segenap kecerdasan yang dimiliki menuju arus masa depan bersama. Gairah kepedulian itu harus terus tumbuh untuk menggapai kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan kemandirian perempuan secara utuh. Jadi, tanggung jawab sosial perempuan (women social responsibility) adalah sebuah panggilan hati nurani perempuan untuk berbuat kebajikan kepada sesama perempuan yang menjadi buruh migran atau tenaga kerja di luar negeri melalui aktivitas yang riil, strategis, dan tulus sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan buruh migran perempuan yang terpadu, bermasa depan cerah, bermartabat, dan cerdas. Woman social responsibility perempuan ini mengarahkan dan menempatkan TKW sebagai agen-agen transformasi sosial, politik dan ekonomi yang penting. Sebagai subjek pemberdayaan dalam pembangunan manusia di era globalisasi. Bukan semata-mata objek penghasil devisa atau komoditas dalam pembangunan manusia.
Penyebab kerentanan buruh migran perempuan atau TKW sehingga menjadi objek “pemerdayaan” atau kekerasan dan pemerasan, menurut Beno Widodo, Koordinator Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) KASBI didasarkan beberapa faktor, yaitu: Pertama, ada masalah di kemauan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Padahal, dalam WCAR (World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia dan Related Intolerance) yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus-7 September 2001 di Durban, Afrika Selatan perlindungan hukum pada buruh migran menjadi salah satu agenda penting. Oleh masyarakat internasional, buruh migran dianggap sebagai entitas sosial yang dalam sejarah kemanusian senantiasa menghadapi tantangan rasialisme, perbudakan, diskriminasi dan bentuk-bentuk tindakan intoleransi lainnya. Patut disesalkan sebagai negara yang menjadi daerah asal buruh migran, Indonesia (terutama pihak Pemerintah RI) tidak pro-aktif dalam perbincangan dan perdebatan masalah buruh migran di pertemuan tingkat dunia tersebut. Kesempatan berpidato Menteri Kehakiman dan HAM RI, Prof DR. Yusril Ihza Mahendra, SH selaku Ketua Delegasi RI di hadapan peserta konperensi, sama sekali tidak menyinggung masalah buruh migran Indonesia. Seakan bukan persoalan krusial. Justru Ms. Gabriela Rodriguez, United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants (Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak buruh migran) memberi perhatian yang sangat khusus terhadap persoalan-persoalan buruh migran Indonesia.
Ketidaksensitifan pemerintah Indonesia bukan itu saja. Presiden Megawati dalam progress report-nya di depan Sidang Tahunan MPR November 2001 menyatakan bahwa telah banyak kemajuan yang dialami dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia (buruh migran Indonesia) di luar negeri, hak-hak perempuan dan hak anak. Pernyataan ini tentu sangat diharapkan jika memang realitasnya demikian. Apabila pernyataan tersebut dihadapkan pada kondisi sebenarnya dari para buruh migran Indonesia di luar negeri, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, sangatlah bertolak belakang. Maka pernyataan itu lebih tepat dianggap sebagai retorika politik belaka.
Kedua, diserahkannya pengiriman buruh migran kepada swasta yang secara pasti hanya mencari keuntungan. Realitas inilah yang menyebabkannya komodifikasi buruh migran perempuan semakin menguat. Nur Harsono dari Migrant Care, memberikan pendapatnya tentang realitas objektivikasi atau komodifikasi buruh migran (perempuan), yakni: Pertama, pemerintah memang sengaja mendorong pengiriman tenaga kerja untuk mengejar target devisa. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, pada tahun 2004, pemerintah menargetkan penempatan 400 ribu TKI dengan remiten 2 milyar dolar AS, sekalipun yang terealisasi adalah penempatan 380.690 TKI dengan remiten 1,9 milyar dolar AS. Kemudian di tahun 2005, pemerintah menargetkan penempatan 700 ribu TKI dengan remiten 3 milyar dolar AS, meskipun yang terealisasi adalah 474.310 TKI dengan remiten 2,93 milyar dolar AS. Lalu, di tahun 2006, pemerintah menargetkan penempatan 700 ribu TKI dengan remiten 3,5 milyar dolar AS, walaupun yang terealisasi adalah 680.000 TKI dengan remiten 3,41 milyar dolar AS. Sementara, di tahun 2007, pemerintah menargetkan penempatan 750 ribu TKI dengan remiten 3,63 milyar dolar AS, sekalipun yang terealisasi adalah 108.732 TKI dengan remiten 0,884 milyar dolar AS. Inilah sebabnya kenapa pemerintah tidak begitu peduli dengan perlindungan hukum, karena kepentingannya hanyalah mengejar devisa.Karena itu, kalau menghitung remitensinya, pemerintah sangat hafal, tapi kalau muncul satu kasus saja, waktu lima bulan belum tentu berhasil menyelesaikannya, karena tidak punya mekanisme penyelesaian kasus. Dengan karakter negara yang demikian, apakah akan ada perbaikan jikalau peran swasta dihapuskan dan pengiriman TKI dilakukan sepenuhnya oleh negara? Rasanya tidak. Ini bukan berarti peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) lebih baik, karena mereka juga terlibat dan menerima keuntungan dari perdagangan manusia ini. Baik negara maupun swasta dalam konteks ini memiliki watak yang serupa, yaitu sama-sama mencari keuntungan dengan memperdagangkan manusia. Yang menjadi persoalan di sini adalah sistem perdagangan manusianya itu sendiri. Kedua, adapun sistem perdagangan manusia ini dimungkinkan karena banyaknya pengangguran di Indonesia. Program TKI sendiri selain ditujukan untuk mendapatkan devisa, juga untuk mengurangi pengangguran. Ini tentu bukan solusi bagi problem pengangguran. Seharusnya, pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan bukannya melakukan perdagangan manusia. (http://politik.kompasiana.com)
Bila memandang diri perempuan sebagai korban dari rencana pemerintah dan pihak swasta bangsanya sendiri, lalu kapan buruh migran perempuan akan menjadi manusia-manusia yang utuh dan unggul, yang siap menghadapi segala tantangan di tengah kepentingan negara ini? Dalam masa pembangunan manusia ini, sudah saatnya perempuan mentransformasi diri, artinya memandang diri sebagai manusia yang dapat eksis dalam kehidupan privat dan publik (sosial, politik, dan ekonomi) yang seksis. Jangan lagi memandang diri sebagai orang-orang yang “siap diberdayakan” secara sosial, politik, dan ekonomi, sehingga terlepas dari bualan-bualan, baik para agen TKI maupun proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan “pengentasan kemiskinan”, “kesejahteraan rakyat”, dan “pembangunan manusia seutuhnya”.
Tulisan ini mencoba menjelaskan secara konseptual tapi popular bagaimana mendorong perempuan untuk bangkit menyatukan tanggungjawab sosialnya agar dapat mengendalikan kehidupan sosial, politik dan ekonominya bukan hanya menjadi sasaran proyek negara atau pemerintah dari sudut pendekatan komunikasi partisipatif dan konsep pemberdayaan : helping some to help themselves yang benar-benar bertumpu pada pembangunan komunitas.
Pendekatan Komunikasi Partisipatif terhadap Tanggung Jawab Sosial Perempuan
Pemicu yang paling signifikan munculnya pemikiran tanggung jawab sosial perempuan (women social responsibility) adalah adanya kesadaran dalam memandang negara yang telah gagal dalam menjadikan buruh migran perempuan sebagai subjek pembangunan sosial, politik, dan ekonomi secara utuh. Karena itu, saya sebagai penulis ingin menyumbangkan saran pada semua perempuan dan pihak-pihak yang peduli pada perempuan di tanah air ini untuk memecahkan masalah program pemerintah atau negara yang tidak pro buruh migran/TKW perempuan melalui pemikiran atau pendekatan komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif ditujukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi TKW dalam arah pemberdayaan sosial, politik, dan ekonomi bangsa di mana esensinya yaitu terciptanya komunikasi dua arah dan hanya terjadi pada partisipan yang sederajat atau setara untuk menciptakan penyebaran (transformasi) dan keseimbangan arus informasi yang sekaligus mendorong munculnya kesadaran, keberanian, dan, kemandirian para buruh migran perempuan tersebut. Pendekatan komunikasi partisipatif (Pambayun, 2009 : 23) ini memiliki lima strategi utama, yaitu: Pertama, conscientization adalah suatu proses bahwa perempuan bukan saja sebagai penerima yang pasif tapi juga subjek yang berpengetahuan yang sangat sadar pada realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang membentuk hidup mereka, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap realitas tersebut. Para buruh migran perempuan dalam konteks ini diharapkan tidak pasif atau pasrah menerima nasibnya sebagai “tenaga perahan” bagi bangsanya. Tapi, sebelum bahkan bila sudah menjadi buruh migran, perempuan harus cerdas setidaknya melek dalam menyikapi dan menghadapi realitas dirinya sebagai perempuan yang memiliki martabat dan hak sebagai manusia bebas. Karena itu, buruh migran perempuan harus dibina dalam melakukan perubahan diri melalui peningkatan diri dalam komunikasi dan bahasa, pemberian wawasan tentang hak-hak dan kewajiban perempuan, persamaan gender, dan penyediaan sarana-sarana yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan buruh migran perempuan, dan optimalisasi keterampilan yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan mereka. Selain itu, melakukan kegiatan–kegiatan yang bersifat praktik seperti melakukan permainan-permainan yang merangsang otak kiri dan kanannya seperti permainan peran (simulasi) dan kerja kelompok. Perangsangan otak kiri dan kanan ini menurut Amir Teungku Ramly (2004:88) akan menyeimbangkan kehidupan manusia secara lebih sempurna, di mana otak kiri merupakan cara berpikir manusia secara rasional dan kognitif dan otak kanan cara berpikir manusia secara emosional atau afektif dan kualitatif, bahkan spiritual. Karena itu, kegiatan ini sangat membantu dalam mendorong keterlibatan buruh migran perempuan secara penuh-mengembangkan dan membangun penyatuan diri dalam kehidupan sosial kepada semua perempuan, kapanpun, dan dalam keadaan apa pun. Karena, di mana pun, bersendiri tidak akan bisa mengubah apa pun.
Dalam pandangan Etzioni (1967) partisipasi berkaitan dengan proses pembebasan manusia, sedangkan proses pembebasan hanya bisa direalisasi oleh manusia bebas. (Dharmawan, 2004:120) Dengan kata lain, penyatuan diri perempuan di komunitas buruh migran perempuan harus difokuskan pada usaha membebaskan mereka dari ketertindasan, ketidaksederajatan, tekanan, ancaman, dan ketakutan dari pihak eksternal yang merasa dominan dan superior seperti orang-orang yang merasa lebih berpangkat, lebih berpendidikan, lebih kaya, dan sebagainya yang lupa pada moto lead to people, walk behind them.
Pengembangan kesadaran buruh migran ini bisa dilakukan dengan cara seperti Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang didirikan di Lebak yang ditujukkan untuk mengatasi semua persoalan kemasyarakatan misalnya pengangguran, kemiskinan, rendahnya mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan, serta rendahnya tingkat kesehatan terutama perempuan dan anak. Untuk keberhasilan terealisasinya integrasi dan partisipasi masyarakat, kita harus belajar dari negara-negara seperti Brazil, Filipina, dan Polandia yang menjadikan lembaga gereja sebagai salah satu sumber penting dari kesadaran dan kekuatan spiritual dan moral organisasi sosial. Di Polandia, Lech Walesa menghimpun dan menyatukan masyarakat untuk mendirikan organisasi buruh solidaritas pemimpin dari gerakan sosial. Bebagai inisiatif masyarakat dengan latar belakang profesi, seni, etnis, budaya, dan sebagainya dapat muncul karena gerakan sosial solidaritas. Organisasi ini berhasil membangun suatu patokan baru dalam pengelolaan masyarakat. (LSM, 2004:148)
Kedua, convergence yaitu suatu pendekatan yang mensyaratkan adanya partisipasi perempuan dalam setiap proses transformasi atau pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Buruh migran perempuan harus memiliki minat atau merasa penting (interest) untuk berafiliasi dalam suatu ikatan atau organisasi yang memberdayakan eksistensinya sebagai perempuan, sehingga aspirasi, perasaan, dan potensi-potensi mereka dapat terakomodasi dalam ranah publik. Julia Cleves Mosse (1996: 224) menyatakan bahwa semua penyakit ketidakadilan gender ini merupakan hasil transformasi. Mereka ditransfer oleh suatu nilai-nilai yang salah tapi dianggap sebagai suatu kebenaran. Karena itu, perempuan harus keluar dari ketergantungan pada pihak lain yang membuatnya menjadi makhluk marginal. Tegasnya, perempuan harus mampu melakukan pemberdayaan diri demi terciptanya transformasi yang diinginkan bukan karena provokasi pihak lain apalagi karena didonasi para kapitalis atau lembaga superior yang seringkali mendiktekan jenis-jenis perubahan atau pemberdayaan perempuan.
Upaya menumbuhkan dan mengintegrasikan dinamika buruh migran perempuan dan perempuan lainnya yang mungkin paling menentukan dalam meningkatkan social intelegence mereka, yaitu :
membuat atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terciptanya fleksibilitas ruang gerak buruh migran perempuan, serta memberikan dan mengakomodasi akses seluas-luasnya bagi aspirasi dan ide-ide positif mereka. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami konsep “hak asasi manusia dan gender oriented” kepada para buruh migran perempuan.
menciptakan komunitas Woman Social Responsibility yang memungkinkan semua buruh migran perempuan dan perempuan lainnya bisa saling mengenal, memiliki rasa persaudaraan yang kuat, serta berkomunikasi dengan akrab atau intens sehingga tidak ada perempuan-perempuan di sekitar kita yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan gender. Salah satu lembaga yang peduli pada kaum buruh migran perempuan adalah komunitas Paguyuban Keluarga Buruh Migran Indonesia (PAKUBUMI) yang merupakan organisasi lokal di Kebumen, dibawah naungan lembanga Migrant Care, Jakarta, yang mayoritas anggotanya adalah mantan TKW. PAKUBUMI berkegiatan dengan membuka stand konsultasi terkait buruh migrant untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dan berbagi pengalaman terkait buruh migran seperti kasus penipuan, diskriminasi, dan perlakukan para penggerak jasa penyalur (PJTKI). Selain itu, kegiatan PAKUBUMI ini dilakukan karena di Kabupaten Kebumen banyak sekali terdapat buruh migran, namun upaya pemerintah Kabupaten Kebumen belum maksimal dalam penanganannya, khususnya perlindungan terhadap buruh migran. Karena itu, mereka membangun jaringan dan bekerjasama dengan stakeholder lain, dalam upaya menegakkan keadilan dan mewujudkan hak perlindungan sebagai warga negara. Lebih dari itu sebagai upaya menjaga komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan PAKUBUMI membuka stand rintisan hasil usaha sendiri seperti pembuatan gula merah, antari, dan cimplung goreng.
memberikan pengalaman proyek-proyek praktis dan cara bagaimana perencanaan atau desain-desain gender oriented/sensitivity yang demokratis dapat dikembangkan bagi buruh migran perempuan di sektor yang berbeda.
Ketiga, public sphere suatu istilah yang dikenalkan Jurgen Habermas diasumsikan Cohen dan Arato , sebagai berikut:
“Adanya integrasi pada institusi-institusi sosial, di mana kelompok-kelompok diinstitusikan, bersifat kolektif, dan asosiasi tersebut tidak boleh ada ancaman, meskipun aktivitas mereka berhubungan dengan politik dan ekonomi. Di sini setidaknya, akan tercipta kemungkinan bahwa kehidupan dunia institusi tersebut dapat mengalirkan “tindakan-tindakan secara lebih terorganisasi dan formal” bukan tindakan-tindakan yang secara nyata tak memiliki tema : ide-ide yang dikomunikasikan antara kehidupan dunia dan sistem dapat menggunakan saluran-saluran lain, bukan menggunakan media uang dan kekuatan, bahkan ini tidak boleh dilakukan”. (Dean dalam Rasmussen, 1996:229)
Khusus dalam aspek perempuan dalam dunia publik, Cohen dan Arato juga menegaskan bahwa:
“Kemanusian yang ideal datangnya dari dunia yang intim seperti keluarga kemudian menyebarkan nilai-nilai moralnya, universalitas, dan antipolitiknya pada kelompok-kelompok dunia publik. Yang paling berperan besar dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan harus muncul untuk merepresentasikan nilai-nilai moral tersebut dan tentu saja harus memiliki kepentingan terhadap nilai-nilai kemanusiaan melaui tindakan–tindakan yang tulus di balik ketidakberdayaan dan penuh ketidakpedulian (selama ini mereka menggangap diri mereka tidak memiliki kekuatan terhadap kepentingan-kepentingan nyata pada khususnya), tanpa harus dianggap mampu dalam meraih universalitas tersebut, karena mereka melakukannya semata-mata karena alasan moral mereka sendiri; kehadiran mereka sebagai audiens di kelompok dunia publik adalah sebagai simbol moral kemanusiaan yang terkait dengan hal-hal di luar mereka, mulai dari semua dunia masyarakat madani yang ada sampai pemerintahan atau negara, adalah bagian dari keluarga. Inilah alasan mengapa perempuan lebih dapat menyimbolkan moral-moral sebagai pola pikir mereka tersebut dibanding meraih label sebagai si peraih dunia. Karena, sudut pandang moral dan alasan-alasan mengapa norma-norma kemanusiaan itu sendiri merefleksikan prolematik posisi perempuan : manusia yang tidak berdaya.” (Dean dalam Rasmussen, 1996:227)
Dalam konsep public sphere ini intinya adalah adanya dialog yang terbuka dan dapat diakses oleh para perempuan sebagai perwujudan communicative action, yaitu:
“Terciptanya pemahaman antarpersona yang didasarkan pada norma kebenaran, ketulusan, keadilan, dan kebebasan. Dihargai atau tidak, persetujuan-persetujuan diajukan tanpa harus ada paksaan di mana pasangan dialog memiliki kesempatan yang sama untuk menebarkan speech act di mana ucapaan-ucapan harus dapat dipahami, benar, sesuai, dan berkata tulus. (Payne, 1997: 112)
Communicative action sebagai payung dari pendekatan komunikasi partisipatif ini adalah pernyataan-pernyataan yang diungkapkan yang secara absah terbuka untuk diteliti secara cermat oleh publik, sehingga akan melahirkan kemungkinan terciptanya konsensus yang ideal yang didasarkan semata-mata pada argumen yang baik. Tentu saja ini akan berimplikasi pada terwujudnya negotiated meanings: tujuan komunikasi terjadi karena keterlibatan dua pihak atau lebih terhadap isu-isu dan permasalahan buruh migran perempuan seperti hukum, komunikasi, politik, sosial, dan ekonomi, khususnya tentang segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan keberadaan buruh migran. Dialog ini untuk merangsang diskusi interaktif di antara sesama perempuan secara bebas sehingga perempuan terbangkitkan kesadarannya untuk memikirkan relasi-relasi yang selama ini sangat diskriminatif, tetapi senantiasa dianggap perempuan sebagai hal yang wajar atau alami. Misalnya, pendirian PPK-Madani (Pusat Pengembangan Komunitas) yaitu suatu lembaga komunitas di Depok yang membangun sebuah rumah aspirasi masyarakat yang ditujukan sebagai upaya penguatan hak-hak masyarakat sipil dan menjadi wadah alternatif media komunikasi sambung rasa antara warga setempat dan para pengambil kebijakan, yaitu pemkot dan DPRD. Hasil yang akan dicapai tentu saja agar buruh migran perempuan dapat menganalisis keadaan diri mereka sebagai perempuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ketidakadilan dalam lingkungan kerja dan masyarakat mereka. Contohnya, eksploitasi tenaga kerja, asuransi, tindakan abuse mulai dari yang verbal sampai yang fisik, pemberian jatah gaji, pendidikan dan kesehatan pada buruh migran perempuan, dan lain-lain.
Keempat grassroot communication yaitu suatu penciptaan media lokal untuk menyebarkan pesan-pesan berupa informasi, edukasi, dan segala bentuk isu perkembangan tentang buruh migran untuk membangun kesadaran dan kecerdasan bagi bagi komunitas buruh migrant perempuan. Misalnya, memberikan pengarahan tentang pembuatan media lokal/warga, media lini bawah (pembuatan publikasi : poster, stiker, buletin, folder, dan kegiatan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas perempuan atau pembuatan kliping), media literacy, dan pelayanan hukum. Selain itu, pembuatan buku panduan bekerja-sama dengan lembaga yang peduli terhadap masalah mereka, menggiatkan diri untuk membaca, menonton, mendengar, membaca atau mengakses media (eketronik dan cetak) dan buku yang relevan dengan masalah perempuan atau gender, dan membacakan buku-buku bagi perempuan yang buta huruf (iliteracy).
Khusus dalam media literacy, seorang buruh migran perempuan harus benar-benar dapat dimelekkan, karena bila ia telah melek terhadap media, maka informasi tentang dunia ini akan dapat terbuka dengan jelas baginya. Media literacy artinya adalah sebuah perluasan kehlian berkomunikasi dan penguasaan informasi yang responsif terhadap perubahan jaman, terutama perubahan yang demikian cepat pada sektor informasi dan media sebagai pembawa pesan-pesan informasinya (Considine, 1995 dalam Yusup, 2010 : 77). Jadi, di sini buruh migran perempuan dapat melek terhadap hak-hak, akses-akses, dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan dirinya.
Kelima, evaluation yaitu langkah untuk melihat dan menilai sejauhmana keefektifan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan aktivitas atau program “tanggung jawab sosial perempuan” terhadap pemberdayaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang berorientasi buruh migran perempuan. Evaluasi partisipasi perempuan terhadap buruh migran memiliki empat tingkat sebagai berikut.
• Information sharing, yaitu tingkat partisipasi yang paling rendah. Di sini para aktivis perempuan berbagi informasi untuk memfasilitasi tindakan kaum buruh migran perempuan. Informasi ini sangat dibutuhkan mereka agar lebih memahami kondisi dan keberadaan mereka sendiri serta penyebab terjadinya disempowerment dalam dunia ketenagakerjaan.
• Consultation, yaitu tingkat partisipasi sebagai sarana ruang tanya jawab seputar permasalah buruh migran sehingga tercipta kepedulian dan tindakan-tindakan positif dengan lingkungan sekitarnya.
• Decision making, yaitu tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari konsultasi di mana para aktivis perempuan di sini dapat memainkan peranannya untuk bersama-sama menentukan desain-desain dan implementasi bentuk-bentuk kampanye pembedayaan dan keadilan gender terhadap buruh migran. Dalam tahap ini buruh migran perempuan tidak boleh diintervensi apalagi didikte dalam menentukan atau merumuskan proses komunikasi partisipatif mereka seperti strategi, arah, tujuan, cara, dan prioritas yang akan dijalankan. Langkah ini yang akan melahirkan bangunan konsensus sosial atau yang disebut societal guidance.
• Initiating action, yaitu tingkat partisipasi dalam proses pemberdayaan yang paling tinggi di mana perempuan dapat ikut mengambil inisiatif dan keputusan dalam proses perubahan yang diharapkan buruh migran perempuan. Chusmeru (2001:50) menegaskan bahwa pemberdayaan berarti pendidikan masyarakat agar dapat mengelola dan menyalurkan energi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya. Karena, energi sosial yang tidak dikelola dan disalurkan secara tepat justru akan menimbulkan anarkis. Dalam tahap ini para buruh migran perempuan harus berperan dalam mewujudkan konsep masyarakat belajar atau concept of societal learning. Caranya adalah dengan mempertemukan top down approach dengan bottom up approach yang selama ini saling kontradiktif. Kontradiksi ini karena adanya perbedaan dalam komunikasi dan pemahaman terhadap; masalah, perumusan tujuan, dan penuangan ide-ide pemecahan praktis di antara masyarakat (bottom) dan para pejabat atau profesional (top). Pihak top yang diwakili para pejabat publik atau pemerintah, profesional, akademisi, bisa juga yang mewakili suatu badan donasi besar mendapatkan pengetahuan melalui abstraksi dunia sosial yang dimanipulasi melalui teori-teori dan metoda ilmiah, sedangkan bottom dalam hal ini buruh migran perempuan mendapatkan pengetahuan secara empiris. Friedman menyatakan bahwa (1974) dua sumber pengetahuan yang kontradiktif ini perlu direstrukturisasi relasi baru, agar tercipta suatu integrasi proses social learning di kedua pihak melalui proses perencanaan yang matang yang disebut sebagai transactive planning (Dharmawan, 2004:121). Di sini para top bisa belajar dari bottom (buruh migran perempuan) dan buruh migran perempuan dapat belajar pengetahuan teknis dari para top. Melaui proses ini maka kedua pengetahuan akan melebur dan menghasilkan perubahan dengan sendirinya. Ide awal para pejabat atau professional adalah mengajari buruh migrant perempuan, kemudian terbalik menjadi “belajar dari buruh migran perempuan”. Sedangkan par aide awal buruh migrant perempuan adalah menjadi pelajar (the learners) kemudian bertransformasi menjadi aksi sosial. Aktivitas “dialog saling belajar” ini akan mendorong buruh migrant perempuan untuk lebih mandiri dan menjadi para inisiator tangguh.
Oleh masyarakat internasional, buruh migran dianggap sebagai entitas sosial yang dalam sejarah kemanusian senantiasa menghadapi tantangan rasialisme, perbudakan, diskriminasi dan bentuk-bentuk tindakan intoleransi lainnya. Padahal, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuannya. Sayangnya, TKI di luar negeri sering menjadi obyek, termasuk perbudakan dan pemaksaan, kekerasan, kesewenang-wenangan, atau kejahatan atas harkat dan martabat manusia yang melanggar hak asasi. Oleh karena itu, program Woman Social Responsibility diharapkan dapat menjadi wujud nada dasar bab pertama dari Deklarasi PBB mengenai hak-hak asasi manusia pada 10 Desember 1948: “Semua insan dilahirkan merdeka dan sama dalam hak dan martabatnya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan kehendak saling bertemu dengan jiwa persaudaraan. Sama seperti yang dinyatakan oleh pengarang Nigeria Wole Soyinka, pemenang hadiah Nobel kesusasteraan, bahwa hak asasi merupakan kerinduan dan cetusan hati manusia yang tulus. Setiap insan mengharapkan penghargaan dari sesama, suami, atasan/majikan, pejabat negara, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Semua buruh migran perempuan menginginkan tanggung jawab (responsibility), baik dari penduduk sekitar maupun penguasa, dan pengadilan atas kejahatan sosial seperti siksaan lahir dan batin, pembunuhan fisik dan karakter (caracter assasin), serta ketidakadilan lainnya. Sementara itu, buruh migran perempuan pun dituntut untuk memiliki jiwa demokrasi, yaitu perasaan akan persaudaraan dan solidaritas antarsesama perempuan, rasa tanggung jawab sosial (social responsibility), serta tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, suku, agama, dan golongan tertentu.
Dengan adanya kekerasan dan eksploitasi secara terus menerus kehidupan buruh migran perempuan dan anak-anak di tengah karut marut negara yang semakin memburuk ini telah menguapkan program-program “bagi perempuan dan anak-anak” dari pemerintah serta lembaga-lembaga peduli perempuan dan anak (organisasi-organisasi nonpemerintah/publik). Namun, di sisi lain, keadaan tersebut dapat memberikan inspirasi (blessing in disguise) bagi pihak-pihak yang peduli dengan masalah buruh migran perempuan dan anak-anak perempuan untuk menemukan hal-hal baru atau bisa juga merekonseptualisasi program-program dan pendekatan-pendekatan pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk diterapkan dalam rangka melengkapi konsep, program, dan pendekatan yang sudah dijalankan. Yang pasti konsep ini bukan sebagai counterpart apalagi sekedar me too concept (ikut-ikutan latah), namun sekedar untuk memuarakan harapan dan sejumput ide sederhana, agar kepedulian tidak menjadi miliki diri sendiri. Kegiatan WSR yang tak lebih sebagai filantropi ini hanyalah media untuk mempraktikan kesadaran sosial dan ketulusan membagi. Karena itu, WSR hendaknya tidak dimaknai sebagai konsep yang hanya menyerukan diskusi, seminar, atau menjadi judul-judulan, tapi program ini merupakan tataran aksi yang menganjurkan agar permpuan peduli pada perempuan lainnya secara tulus dan tanpa henti.
Akhirnya, WSR adalah jendela untuk nurani berkata dan wahana komunikasi semua perempuan untuk peduli pada sesama. WSR hanyalah perantara, di mana praktik kecerdasan sosial dan kecerdasan komunikasi diterapkan. Spirit dan pendekatan komunikasi semacam ini akan menghalau individualisme, sikap serba cuek dengan lingkungan sekitarnya. Jika semangat komunikasi partisipatif telah mendarah-daging pada setiap perempuan, maka kodrat sosial sebagai pembawaan sejak lahir akan kembali menemukan harmonisasinya di tengah dunia yang fana ini. Kehidupan yang merupakan berkah dari Allah SWT dengan fitrah perempuan sebagai manusia akan saling menyatu membangun perempuan yang sejahtera di masa kini dan nanti. Semoga!
Daftar Pustaka
– Chusmeru, Drs, M.Si. Komunikasi di Tengah Agenda Reformasi Sosial Politik. Bandung. Penerbit PT Alumni. 2001
–
– Dean, Jody. “Civil Society: Beyond Public Sphere.”(editor) Rasmussen, David M. The Handbook of Critical Theory. USA. Blackwell. 1996
– Dharmawan, HCB (editor). Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan. Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2004
– Mosse, Julia Cleves. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta. Rifka Anisa Woman’s Crisis Centre dan Pustaka Pelajar. 1996
– Oey, Mayling. “Perubahan Pola Kerja Kaum Perempuan di Indonesia Selama Dasawarsa 1970: Sebab dan Akibatnya” dalam Liza Hadiz (editor), Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru. Jakarta. LP3S. 2004
– Pambayun, Ellys Lestari. Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya. Bandung. Penerbit Nuansa. 2009
– Payne, Michael. A Dictionary of Cultural and Critical Theory. USA. Blackwell Publisher. 1997
– Ramly, Amir Teungku. Pumping Talent. Jakarta. Pustaka Inti. 2004
– Susilo, Wahyu. “Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Indonesia” dalam Jurnal Perempuan, Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan, Edisi 26 Tahun 2002
– Unger, Rhoda & Crawford, Mary. Women and Gender: A Feminist Psychology. USA. McGraw Hill Publishing.1992
– Yusup, Pawit M. Komunika Instruksional: Teori dan Praktik. Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2010
– Kompas, 14 Nopember 2009
– okezone.com
– http://arsip.indipt.org/2010/12/16/stand-konsultasi-buruh-migran
– http://tkw-korea.blogspot.com/2011/01/perlindungan-tenaga-kerja-migran.html
– http://www.trunity.net/infidjakarta/articles/view/160705
– http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-07,id.html
– http://news-monitor.ecosocrights.org/node/128192
– http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/payung-hukum-bagi-pekerja-migran-IIndonesia
– http://politik.kompasiana.com/2010/12/15/program-tki-program-perdagangan-manusia
*Tulisan ini diterbitkan dalam Jurnal Ilmu dan Budaya (Unas Jakarta) Vol.5 No.26 Juni 2012